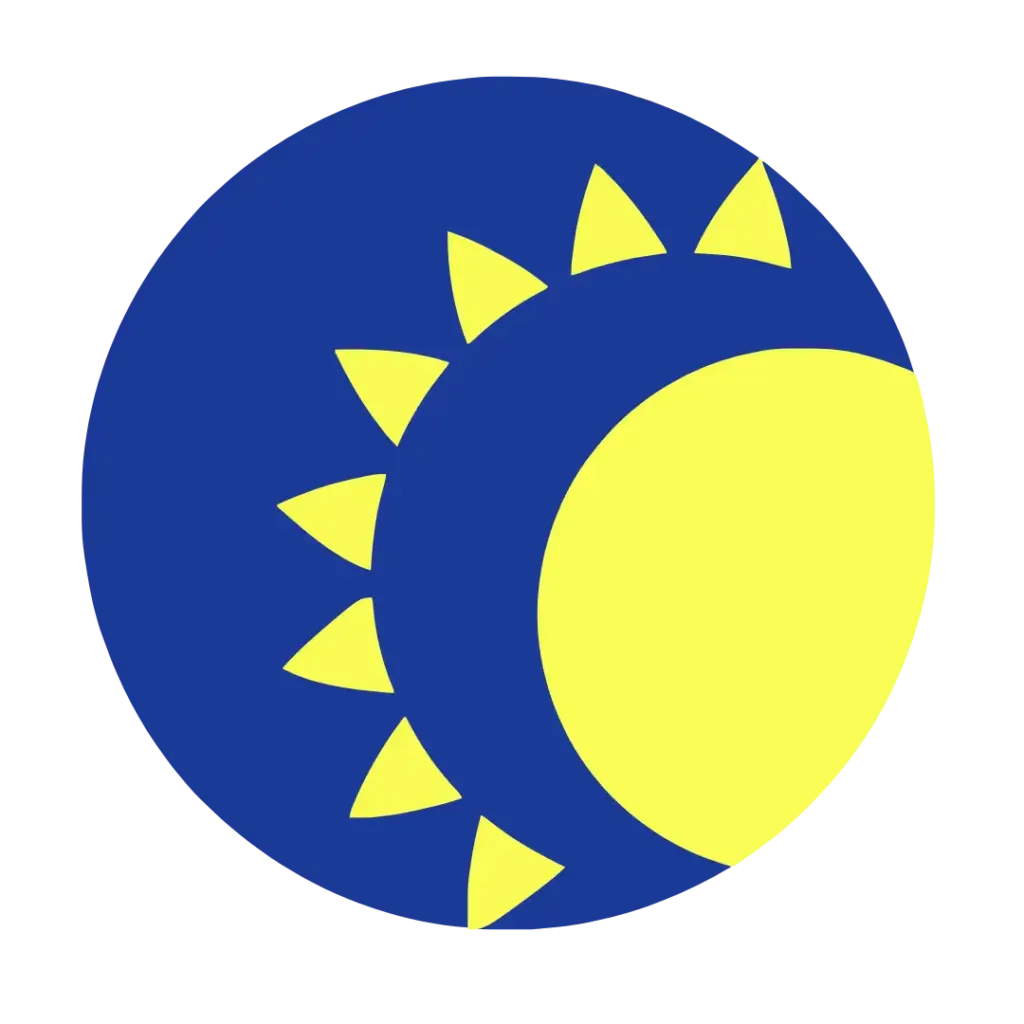Sejak perang berkecamuk di Sudan, isu gencatan senjata kemanusiaan terus berulang, terutama saat krisis kemanusiaan mencapai puncaknya. Namun, usulan gencatan senjata kali ini muncul dalam konteks yang berbeda dan berbahaya, menyusul dugaan genosida dan pembersihan etnis oleh milisi Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di El-Fasher, Darfur.
El-Fasher, yang dulunya menjadi simbol keberagaman dan koeksistensi, kini menjadi kota yang hancur dan ditinggalkan penduduknya. Setelah kejadian ini, komunitas internasional kembali mengusulkan gencatan senjata kemanusiaan sebagai solusi. Hal ini memerlukan analisis politik yang cermat, tidak hanya terpaku pada slogan moral, tetapi juga mempertimbangkan motif dan potensi konsekuensinya, terutama terkait persatuan geografis, sosial, dan politik Sudan.
Dalam budaya populer, ada pepatah: “Jika orang miskin makan ayam, pasti orang miskin itu sakit atau ayamnya yang sakit.” Pepatah ini menggambarkan kecurigaan politik yang wajar terkait waktu usulan gencatan senjata ini. Gencatan senjata untuk tujuan kemanusiaan, pada prinsipnya, bertujuan meringankan penderitaan warga sipil dan membuka jalan menuju akhir konflik. Namun, dalam kasus Sudan, yang menimbulkan kekhawatiran adalah usulan gencatan senjata ini muncul setelah bencana terjadi, bukan sebelumnya. RSF secara tegas menolak komitmen kemanusiaan, termasuk melindungi rumah sakit dan mengamankan koridor aman bagi warga sipil untuk mengungsi.
Organisasi kemanusiaan telah beroperasi di sebagian besar wilayah Sudan, termasuk Darfur, meskipun ada kompleksitas keamanan dan tanpa adanya gencatan senjata yang sah dan ditandatangani. Hal ini menimbulkan pertanyaan: Mengapa gencatan senjata didorong sekarang? Dan untuk kepentingan siapa gencatan senjata ini diusulkan pada saat ini? Kontradiksi ini membuka pintu bagi kecurigaan bahwa tujuannya melampaui masalah kemanusiaan, dan lebih kepada membentuk kembali realitas politik dan geografis negara.
Sejarah modern penuh dengan contoh di mana gencatan senjata kemanusiaan berubah dari alat de-eskalasi menjadi awal fragmentasi dan pemisahan diri. Di Sahara Barat, Libya, Somalia, Yaman, dan Sudan Selatan, gencatan senjata tidak selalu menjadi jembatan menuju perdamaian; lebih sering, mereka menjadi tahap transisi menuju pembagian negara dan erosi kedaulatan. Dalam konteks Sudan, khususnya, Operasi Lifeline Sudan yang diluncurkan oleh PBB pada tahun 1989 menjadi contoh bagaimana aksi kemanusiaan digunakan sebagai titik masuk politik, yang akhirnya berujung pada pemisahan Sudan Selatan melalui referendum setelah proses normalisasi pemisahan yang panjang. Situasi saat ini jauh lebih berbahaya dan kompleks. Ini bukan tentang pemerintah yang bernegosiasi dengan gerakan politik yang memiliki tuntutan nasional, tetapi skenario yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana dua pihak mengklaim mewakili “pemerintah” dalam satu negara: Pemerintah sah Sudan, dan RSF, yang berusaha mendirikan entitas paralel.
Negosiasi antara “dua pemerintah” dalam satu negara tidak hanya belum pernah terjadi sebelumnya di Sudan; ini merupakan jebakan politik yang serius yang bertujuan mengekstrak pengakuan kekuatan de facto di bawah payung gencatan senjata. Tindakan penandatanganan bersama memberikan pihak pemberontak kesetaraan dan legitimasi, yang secara fundamental bertentangan dengan pengorbanan besar yang dilakukan oleh rakyat Sudan dalam membela persatuan dan kedaulatan negara. Jalur ini merupakan pelanggaran langsung terhadap prinsip-prinsip inti yang diperjuangkan para martir dan para janda: prinsip persatuan, prinsip pemerintahan terpadu dan legitimasi konstitusional, dan prinsip kesatuan institusi militer.
Kekhawatiran semakin dalam dengan kurangnya transparansi dalam proses gencatan senjata. Mengapa negosiasi dilakukan secara tertutup? Mengapa rakyat Sudan tidak tahu apa yang disepakati atas nama mereka? Bagaimana negara asing dapat bernegosiasi atas nama orang-orang yang berdarah-darah karena perang dan pengungsian? Siapa yang lebih berhak mengawasi upaya perdamaian selain rakyat sendiri? Apakah ada prioritas yang lebih besar daripada memimpin perang yang sedang berlangsung di mana semua orang terlibat? Yang lebih mengkhawatirkan adalah pihak yang “memegang pena” dalam proses politik adalah pihak yang sama yang “memegang senjata”, melakukan pembunuhan dan pembersihan etnis.
Pembacaan komprehensif terhadap peristiwa menunjukkan bahwa gencatan senjata ini lebih mungkin menjadi titik masuk untuk membongkar negara Sudan daripada jembatan untuk menyelamatkannya. Ini dapat menyebabkan penguatan divisi: zona pengaruh, banyak tentara, mata uang yang berbeda, bank sentral paralel, kementerian luar negeri yang bersaing, dan paspor yang saling bertentangan. Tidak ada yang membantah prioritas untuk meningkatkan kondisi kemanusiaan dan melindungi warga sipil. Namun, gencatan senjata yang didorong hari ini dapat membawa stabilitas sementara dengan mengorbankan harga strategis yang menghancurkan: erosi persatuan Sudan.
Tugas nasional menuntut tingkat kewaspadaan dan kehati-hatian tertinggi, agar gencatan senjata tidak berubah menjadi jebakan politik, mendorong proyek disintegrasi negara. Harapan tetap tertumpu pada kesadaran rakyat Sudan dan kemampuan mereka untuk bersatu dalam menghadapi momen yang menentukan ini, dalam membela satu tanah air, satu tentara, dan satu negara, yang menolak partisi dan perwalian, hanya menerima kehendak rakyatnya melalui sistem dan kerangka kerja yang tidak melibatkan perebutan dengan paksa atau pemaksaan realitas dengan todongan senjata. Situasi di Sudan ini menjadi pelajaran berharga bagi negara lain, termasuk Indonesia, mengenai pentingnya menjaga persatuan dan kedaulatan negara di tengah konflik dan kepentingan asing yang mungkin terlibat.
Dikutip dari Al Jazeera.